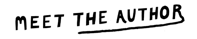Bagaimana kolonialisme membentuk standar kecantikan di Indonesia
(Courtesy of Aninda Annisa)
Saya menyadari bahwa, sepanjang hidup saya, saya terbiasa menerima gambaran kecantikan ideal yang begitu rasis dengan mengagungkan kulit putih dan meremehkan kulit gelap.
Saat berusia 21 tahun, saya belajar di luar negeri di Swedia selama satu semester dan tinggal jauh dari Indonesia untuk pertama kalinya. Saya masih ingat, setibanya di Swedia, saya mendatangi toko kebutuhan sehari-hari dan mengambil beberapa losion tubuh sembari mencari kata yang akrab saya jumpai “memutihkan” dan “mencerahkan,” yang kerap menghiasi label losion di negara asal saya. Namun, semua produk di toko itu hanya menyebutkan fungsi melembapkan kulit, tidak satu pun menyebutkan mencerahkan.
(Courtesy of Aninda Annisa)
Sekembalinya di asrama, untuk pertama kalinya saya menyadari betapa tidak adilnya masyarakat Indonesia yang memaksa wanita untuk menggunakan produk pencerah kulit. Saya menyadari bahwa, sepanjang hidup saya, saya terbiasa menerima gambaran kecantikan ideal yang begitu rasis dengan mengagungkan kulit putih dan meremehkan kulit gelap — dan ini bukan norma yang berlaku di negara lain. Di Indonesia, saya terbiasa mendengar bahwa tabir surya harus selalu digunakan agar kulit saya tidak berubah menjadi gelap dan saya harus menggunakan produk pemutih pada wajah dan tubuh. Saya pun ingat bahwa saya pernah menangis saat mantan pacar saya membandingkan saya dengan gadis yang namanya sama dengan saya, namun mengatakan bahwa gadis itu jauh lebih cantik dari saya karena kulitnya yang putih. Tetapi di Swedia, teman saya mengatakan bahwa saya cantik apa adanya.
Di mana awal segala kesalahpahaman ini? Bagaimana orang Indonesia meyakini bahwa memiliki kulit Putih atau merupakan keturunan Kaukasia menjadikan seseorang lebih cantik? Mengapa wanita di Indonesia menggunakan produk pemutih agar kulit menjadi lebih cerah? Apakah kesalahpahaman ini bermula dari industri kecantikan, ataukah mereka hanya berusaha memenuhi permintaan pasar? Dari mana sebenarnya kesalahpahaman ini berasal?
Jawabannya adalah: kolonialisme.
Berawal dari abad ke-16, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonialisme selama lebih dari 350 tahun. Saat Perusahaan Hindia Timur Belanda (Dutch East India Company) tiba di Indonesia pada awal abad ke-17, mereka menciptakan hierarki sosial dalam upaya mengendalikan populasi Indonesia. Mereka menempatkan warga Belanda sebagai kalangan atas, warga Tionghoa di tengah, dan warga Pribumi di strata terbawah. Struktur ini kian mengukuhkan superioritas orang berkulit Putih dalam segala hal — tak terkecuali dalam standar kecantikan. Preferensi akan kulit Putih dan karakter yang dimilikinya ini tidak kunjung sirna hingga saat ini, sekalipun Indonesia tidak lagi di bawah penjajahan Belanda.
Tumbuh dewasa di Indonesia, remaja wanita terbiasa mendengar bahwa kulit putih berarti kulit yang cantik. Melalui produk kecantikan, periklanan, papan reklame, kelas kecantikan, dan lain sebagainya, masyarakat terus menggaungkan pesan ini. Sebagian besar remaja wanita di Indonesia menggunakan riasan agar terlihat “Putih.” Praktik ini membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Saya pikir karena saya tidak memiliki kulit yang Putih, saya tidak akan pernah terlihat cantik. Saya tidak dapat menerima diri saya dan kerap menangis karena kekurangan saya. Saya pun tahu bahwa ada banyak wanita lain di luar sana yang juga merasakan hal ini.
“Saya menyadari bahwa, sepanjang hidup saya, saya terbiasa menerima gambaran kecantikan ideal yang begitu rasis dengan mengagungkan kulit putih dan meremehkan kulit gelap.”
Tinggal di Swedia — dengan banyaknya pendatang dengan berbagai warna kulit — menyadarkan saya bahwa apa pun warna kulit Anda, Anda cantik apa adanya. Sejak saat itu, saya berusaha menghindari produk yang bertujuan untuk “mencerahkan kulit”. Semua produk yang saya gunakan untuk wajah dan tubuh secara spesifik menjawab permasalahan kulit saya. Saya menggunakan produk yang membantu meredakan jerawat alih-alih mencerahkan wajah saya. Saya menggunakan produk yang melembapkan kulit alih-alih menjadikannya putih. Keluarga saya mengetahui perubahan terhadap diri saya dan saya pun menjelaskan alasannya. Saat bertemu teman-teman saya, kami kerap bertukar produk yang tengah kami gunakan untuk membantu mengatasi masalah kulit masing-masing. Dalam perbincangan kami, saya mengatakan bahwa kita harus berhenti memilih produk hanya untuk terlihat “Putih”. Kita harus lebih mencintai warna kulit yang kita miliki.
Inilah saatnya Indonesia menerima wanita apa adanya dan menghilangkan stereotip kecantikan ini. Apa pun warna kulitnya, semua wanita cantik. Apa pun bentuk tubuh, warna rambut, tekstur rambut, dan warna matanya, semua wanita menarik. Masyarakat harus berhenti mengotak-ngotakkan dan mulai menghargai satu sama lain. Kolonialisme sudah berakhir ratusan tahun lalu; kita pun harus berhenti mengagungkan asumsi “Putih itu cantik, cantik itu Putih”. Dari Sabang sampai Merauke, orang Indonesia memiliki berbagai macam warna kulit dan mereka semua cantik.
 Read more
Read more